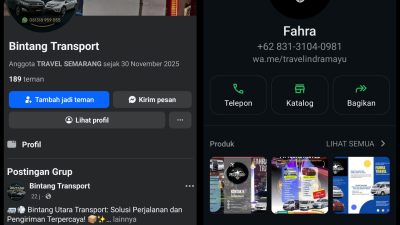Oleh: Teguh Eko Prasetyo
(DPP IMM Bidang Kajian dan Pengembangan Keilmuan)
Mediapenanews.net – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dalih efisiensi anggaran sejatinya bukan upaya menyelamatkan demokrasi. Sebaliknya, ia justru menyederhanakan demokrasi dengan cara paling berbahaya: mengeluarkan rakyat dari proses pengambilan keputusan politik.
Di balik bahasa teknokratis tentang penghematan biaya, tersembunyi pilihan politik yang sangat mendasar—apakah negara masih menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, atau justru mulai menganggap partisipasi publik sebagai beban yang bisa dinegosiasikan.
Hak memilih pemimpin bukanlah fasilitas tambahan yang bisa dicabut demi efisiensi. Ia merupakan hak konstitusional warga negara yang melekat pada prinsip kedaulatan rakyat. Mengorbankannya atas nama penghematan anggaran berarti mempreteli demokrasi secara sistematis, bukan memperbaikinya.
Masalah tingginya biaya politik sejatinya tidak bersumber dari partisipasi rakyat. Akar persoalannya justru terletak pada praktik politik yang tidak sehat: politik uang, mahar pencalonan, kampanye yang serba mahal, hingga transaksi kekuasaan pascapemilu. Ironisnya, alih-alih membenahi penyakit ini, sebagian elite politik memilih jalan pintas dengan memangkas peran rakyat.
Jika efisiensi benar-benar menjadi tujuan, solusi semestinya diarahkan pada pembenahan tata kelola pendanaan politik, transparansi dan pembatasan biaya kampanye, penegakan hukum pemilu yang tegas, serta pendidikan politik yang serius bagi elite dan partai. Namun langkah-langkah tersebut menuntut komitmen, integritas, dan perubahan perilaku—sesuatu yang jauh lebih sulit dibanding memindahkan proses pemilihan ke ruang tertutup DPRD.
Klaim bahwa pemilihan melalui DPRD lebih murah dan lebih stabil pun patut dipertanyakan. Biaya politik tidak serta-merta hilang; ia hanya berpindah dari ruang publik yang relatif terbuka dan dapat diawasi, ke ruang lobi elite yang tertutup dan sulit dilacak. Uang tetap bekerja, tetapi tanpa kontrol rakyat.
Dalam mekanisme semacam ini, kepala daerah akan lebih bergantung pada konfigurasi kekuatan partai di parlemen ketimbang mandat langsung dari warga. Akuntabilitas pun bergeser—bukan lagi kepada publik, melainkan kepada elite politik. Pergeseran ini membuka ruang kompromi kekuasaan yang berpotensi mengabaikan kepentingan rakyat banyak.
Menyebut proses tersebut sebagai “pemilihan umum” menjadi problematis ketika rakyat sama sekali tidak dilibatkan. Demokrasi tanpa partisipasi publik hanya menyisakan prosedur hukum yang kering, tanpa roh dan makna substantif.
Efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan dalih untuk menggerus hak-hak dasar warga negara. Jika logika ini diterima, maka seluruh hak konstitusional berpotensi dinegosiasikan setiap kali dianggap mahal atau merepotkan. Ini merupakan preseden berbahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia.
Demokrasi memang tidak selalu rapi, murah, dan nyaman. Ia gaduh, melelahkan, dan penuh ketegangan. Namun kegaduhan itulah tanda bahwa rakyat masih memiliki ruang untuk menentukan arah kekuasaan. Demokrasi yang sunyi dan terkendali justru patut dicurigai—karena sering kali menandai hilangnya substansi kedaulatan rakyat.
Pada akhirnya, perdebatan ini bukan sekadar soal mekanisme pemilihan kepala daerah. Ia adalah soal keberpihakan negara: apakah tetap percaya pada kedaulatan rakyat, atau memilih kenyamanan kekuasaan dengan kontrol publik yang minimal. Ketika rakyat dikeluarkan dari proses pengambilan keputusan, yang tersisa bukanlah efisiensi, melainkan kekuasaan yang semakin menjauh dari pemilik kedaulatan sejati.